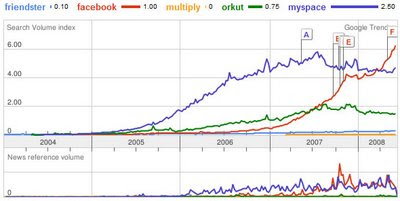Dalam kemajuan teknologi komunikasi informasi, terutama dalam konteks Indonesia dengan lalu lintas data blog terbesar untuk ukuran global sebagai salah satu dari 30 kota dunia dengan blog yang paling sibuk, ada fenomena penting yang lolos dari perhatian kita.
Kemajuan teknologi memasuki abad informasi, ada upaya kita untuk tidak bisa memisahkan batasan- batasan yang berlaku sesuai kaidah hukum, seolah-olah menulis blog, melakukan aktivitas jurnalisme warga (citizien journalism), menjadi moderator, dan aktivitas di jejaring internet lainnya tidak bisa dihukum.
Dan fenomena ini muncul dalam kehidupan kita, ketika tuduhan terhadap seseorang melakukan korupsi di salah satu situs Web dimasukkan ke mailing list Forum Pembaca Kompas menyebabkan moderator forum dipanggil sebagai saksi oleh kepolisian untuk diperiksa. Persoalan muncul ketika terjadi pertanyaan apakah moderator mailing list tidak bertanggung jawab atas materi isi yang dibahas di forum tersebut dan bebas nilai?
Sebuah situs Web sejenis jurnalisme warga menulis laporan berdasarkan pengalamannya bertemu kenalannya, menyebutkan partai politik meminta uang kepada sebuah perusahaan agar tidak kena hak angket oleh DPR yang bisa menghambat jalannya initial public offering (IPO) perusahaan itu.
Tulisan ini juga menulis nama seorang anggota DPR dari partai yang meminta uang tersebut, yang datang ke perusahaan tersebut meminta uang dalam jumlah besar mulai dari Rp 6 miliar sampai turun ke jumlah Rp 1 miliar. Semua ditulis berdasarkan penuturan kenalan penulis.
Tulisan di situs Web jurnalisme warga ini kemudian diteruskan ke mailing list Forum Pembaca Kompas, kemudian diteruskan lagi oleh salah satu anggota forum ke anggota DPR yang disebut namanya. Akibatnya, anggota DPR ini menuntut penulis tulisan yang ada di situs Web dan forum tersebut, dan pihak kepolisian menjadikan moderator forum sebagai saksi.
Pipa dua arah
Ini persoalan rumit, melibatkan banyak aspek memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi informasi yang menghadirkan fenomena baru dan tanpa preseden sama sekali. Di sisi lain, persoalan ini menjadi ujian penting untuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)yang mengatur keseluruhan hidup dan aktivitas kita di jejaring internet.
Persoalan ini penting untuk mengukur apakah demokrasi yang kita jalankan di jejaring internet adalah bebas nilai yang semaunya mencemarkan nama baik, menuduh seseorang, atau memfitnah atas nama kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mengemukakan kebenaran?
Setelah tergulingnya Orde Baru, demokrasi dan kemajuan teknologi komunikasi informasi adalah satu persoalan dalam dua sisi sebuah koin. Sisi pertama, demokrasi dan reformasi yang menggebu-gebu memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi informasi, serta menghadirkan empat presiden yang berbeda-beda, ternyata tidak mampu mengusir kezaliman dan kejahatan diri kita semua dalam cara berpikir dan korupsi.
Artinya, campuran demokrasi dan kemajuan teknologi komunikasi informasi ternyata tidak mengubah apa-apa secara fundamental dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, dan berinformasi. Kita memang berhasil dalam menikmati kebebasan berpendapat seenaknya, lebih enak dari negara-negara Barat sebagai kampiun kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Sisi kedua, teknologi komunikasi informasi tercampur demokrasi-reformasi, menghasilkan apa yang disebut sebagai jurnalisme warga, yang secara definisi dirumuskan sebagai memainkan peranan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisa, serta diseminiasi berita dan informasi.
Artinya, dalam era demokrasi-reformasi berbasis informasi sekarang ini semua warga di negara kepulauan Nusantara ini adalah konsumen, semua orang adalah distributor, semua warga menjadi agregator, dan semua orang adalah produser. Menurut CEO Reuters Tom Glocer, dari kantor berita Inggris ternama dan disegani di dunia, kita hidup dalam era pipa dua arah. Glocer menajamkan pengertiannya bahwa semua orang memiliki potensi sebagai mitra dan sekaligus sebagai kompetitor.
Kekisruhan informasi
Kita memahami sedalam-dalamnya, kemajuan teknologi komunikasi informasi yang sekarang menjadi bagian kehidupan digital kita sehari-hari memang telah menghadirkan pilihan baru mengakses informasi seluas-luasnya. Jejaring internet memungkinkan semua warga negara Indonesia untuk memberikan sumbangsih kepada jurnalisme tanpa pelatihan formal.
Jurnalisme warga yang sekarang didengung-dengungkan oleh siapa saja yang memanfaatkan kemajuan jejaring internet, baik memiliki situs Web sendiri dan situs blog yang menjadi fenomena penting kemajuan internet Indonesia, berkembang begitu liar dan berdalih dilindungi oleh undang-undang pers ketika terjadi kekisruhan diseminasi informasi seperti yang terjadi dalam kasus di atas.
Yang harus dipahami, dan ini tidak tercermin dalam perkembangan jurnalisme warga di Indonesia, jurnalisme akan selalu memiliki seperangkat prinsip- prinsip, seperti memeriksa ulang sumber informasi dan memisahkan komentar dan pelaporan. Pada media massa tradisional, kaidah ini mengalami penyaringan sangat ketat dengan berbagai mekanisme news room.
Pada jurnalisme warga, yang muncul seringkali adalah one reporter journalism yang tidak bisa membedakan melaporkan berita dan menjadi berita. Akibatnya, terjadinya tuduh menuduh yang berakibat tercemarnya nama baik seseorang. Ketika menjadi persoalan hukum, bagaimana mungkin one reporter journalism berdalih dan berlindung pada hak jawab yang diatur oleh undang-undang?
Yang tidak kalah menarik adalah tulisan dimuat di situs Web dianggap sebagai kebenaran hakiki dan tidak dimiliki oleh media tradisional. Padahal, mungkin saja informasi yang sama yang ditulis pada situs Web dimiliki oleh reporter di media tradisional, tetapi disimpan di komputer karena masih mentah dan belum layak disajikan sebagai konsumsi umum.
Menjaga kepercayaan
Kemajuan jejaring internet memang telah memberikan pilihan diseminasi informasi yang berlawanan dengan arus utama yang selama beberapa dekade dikuasai oleh media tradisional, mulai dari surat kabar, radio, sampai televisi. Internet menghadirkan tidak hanya jurnalisme warga yang berupaya untuk menjadi alternatif informasi mainstream, mulai dari blog yang masuk dalam kategori user-created-content (UCC).
Sesadar-sadarnya kita memahami pilihan diseminasi informasi dengan semakin luas dan cepat akses jejaring internet, menjadi ancaman penting bagi informasi mainstream yang bekerja dalam konteks industri informasi. Namun, ini tidak berarti bahwa pilihan informasi di jaringan internet bisa dikategorikan sebagai karya jurnalistik yang bebas nilai dan terlepas dari jerat hukum yang berlaku.
Oh Yeong-ho, pendiri Ohmynews sebagai pelopor utama citizen journalism di dunia asal Korea Selatan, secara tegas mengakui bahwa menulis sebuah berita membutuhkan waktu yang lebih lama dari hanya sekadar memberikan sebuah komentar atau melakukan posting pada situs blog.
Dalam pencemaran nama seseorang memang tidak ada pilihan untuk dilakukan pemeriksaan, karena ”kerusakan sudah terjadi” dan harus ada yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Sekaligus menguji dan memperbaiki berbagai undang- undang dan peraturan hukum mengantisipasi kemajuan teknologi komunikasi informasi.
Memang menjadi persoalan, apakah moderator sebuah mailing list juga ikut terlibat di mata hukum ketika terjadi kerusakan tersebut? Apakah seorang moderator bisa masuk bui karena dituduh ikut menyebarkan pencemaran nama baik hanya karena memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi informasi?
Ketika UU ITE digelar, persoalan ini menjadi perdebatan hangat oleh siapa saja. Dan seharusnya perdebatan ini dilanjutkan untuk bisa mencapai apa yang kita sepakat satu-satunya bebas nilai itu adalah kebenaran yang hakiki. Di tengah kemajuan internet sekarang ini, informasi yang mana yang bisa dipercaya atau informasi bagaimana yang akurat? Kita tahu kalau kepercayaan pembaca itu sangat rentan sehingga perlu proses panjang untuk bisa menjaga kepercayaan itu.
Sumber :
Rene L Pattiradjawane
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/08/01250183/jurnalisme.warga.teknologi.dan.bebas.nilai
8 September 2008
Sumber Gambar:
http://www.balebengong.net/wp-content/uploads/2009/11/foto-poster-sloka-1024x680.jpg